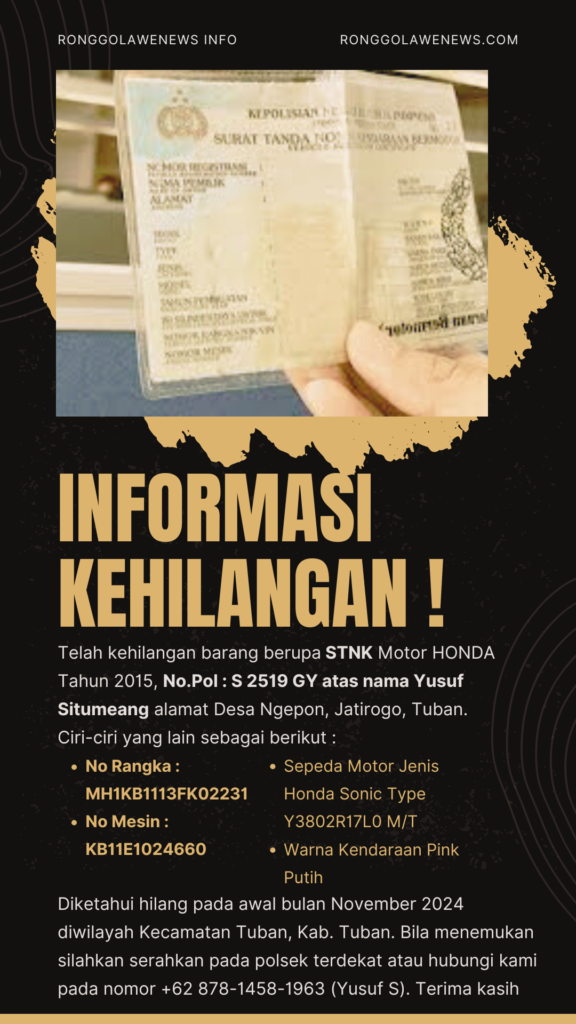Surakarta, Ronggolawe News — Riuh lembut gamelan di dalam Keraton Surakarta pagi itu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar prosesi adat. Di tengah suasana duka atas wafatnya Paku Buwono XIII, suara lantang seorang muda berusia 23 tahun menandai babak baru bagi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dialah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, yang kini menapaki takhta sebagai Paku Buwono XIV — raja termuda dalam sejarah panjang Keraton Solo.
Namun, di balik kidung sakral dan bau dupa yang membumbung di Pendapa Sasana Sewaka, tersimpan pertanyaan yang tak terucap: Apakah darah muda sang raja baru mampu menyalakan kembali bara kejayaan Mataram yang mulai pudar?
Dari Gunung ke Takhta
Sejarah mencatat, tak banyak putra mahkota yang tumbuh di bawah langit pegunungan. Tapi Hamangkunegoro berbeda. Ia mendaki Gunung Lawu sejak usia dua tahun, dipandu langsung oleh ayahandanya, Paku Buwono XIII. Gunung bukan sekadar tempat, tapi sekolah pertama bagi sang raja muda — tempat ia belajar diam, tunduk, dan mengenali arah angin kehidupan.
Kecintaannya pada alam menjadi jejak spiritual yang sulit dipisahkan dari darah biru yang mengalir di tubuhnya. Bagi Hamangkunegoro, mendaki gunung dan memimpin kerajaan adalah dua hal yang sama: keduanya menuntut napas panjang, keseimbangan, dan keteguhan hati.
Seni, Kearifan, dan Daya Tahan
Dalam catatan Ronggolawe News, Hamangkunegoro bukan sekadar simbol pewaris tahta. Sejak usia delapan tahun, ia menari di bawah lampu pagelaran — memerankan Gathotkaca dalam lakon klasik di Sasana Sumewa. Ia tumbuh di antara gamelan dan pusaka, antara filsafat Jawa dan disiplin akademik modern.
Berbekal pendidikan dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta hingga FISIP Universitas Gadjah Mada, ia menempuh jalur panjang untuk menyeimbangkan logika Barat dengan ruh Timur. Bagi Keraton Solo yang lama terjebak dalam formalitas upacara, munculnya sosok muda dengan semangat keterbukaan ini bagaikan hembusan angin baru dari arah Lawu.
Ikrar yang Menggema di Tengah Kabut Keraguan
Dalam suasana berkabung, Rabu Legi 14 Jumadilawal 1959 (5 November 2025), ia melafalkan ikrar yang menembus dinding sejarah:
“Ingsun… hanglintir kaprabon Dalem minangka Sri Susuhunan Karaton Surakarta Hadiningrat, kanthi sesebutan Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Paku Buwono XIV.”
Namun, sebagaimana sejarah panjang Kasunanan, setiap ikrar selalu diikuti bayangan perdebatan. Sebagian pihak menyebut penobatan itu terlalu cepat, mengingat paugeran (aturan adat) baru memperbolehkan pengangkatan raja setelah 40 hingga 100 hari masa hening.
Di sisi lain, muncul sosok Kanjeng Gusti Panembahan Tedjowulan, paman mendiang PB XIII, yang menyatakan diri sebagai pelaksana tugas (Plt.) Keraton. Ia dikenal sebagai figur senior dan pernah menjadi tangan kanan raja. Keberadaannya menimbulkan tafsir ganda di balik dinding istana — antara kesinambungan dan perebutan wewenang.
Raja Muda di Persimpangan Zaman
Dalam pandangan beberapa abdi dalem, Hamangkunegoro adalah simbol perubahan: raja muda yang tidak lahir di tengah perebutan kekuasaan, tapi di tengah kebingungan identitas kebudayaan. Ia memahami dunia digital, namun juga hafal urutan pusaka. Ia mencintai ritual leluhur, namun juga terbuka pada kritik publik.
Ronggolawe News mencatat, tantangan terbesar PB XIV bukanlah mempertahankan kekuasaan, melainkan mengembalikan makna Keraton sebagai sumber nilai, bukan sekadar simbol upacara.
Catatan Redaksi Ronggolawe News
Langit Keraton Surakarta memang tengah berubah. Di antara kabut Lawu dan tembok batu bata tua, berdiri seorang raja muda yang membawa dua dunia: masa lalu yang sarat makna dan masa depan yang menuntut keberanian.
Apakah Hamangkunegoro akan menjadi “raja pewaris” atau “raja pembaharu”?
Waktu, sejarah, dan rakyat Jawa-lah yang akan menjawabnya.
Reporter: Tim Investigasi Budaya Ronggolawe News
Editor: Anto Sutanto
Foto Dokumentasi: Arsip Karaton Surakarta & Ronggolawe Visual Unit