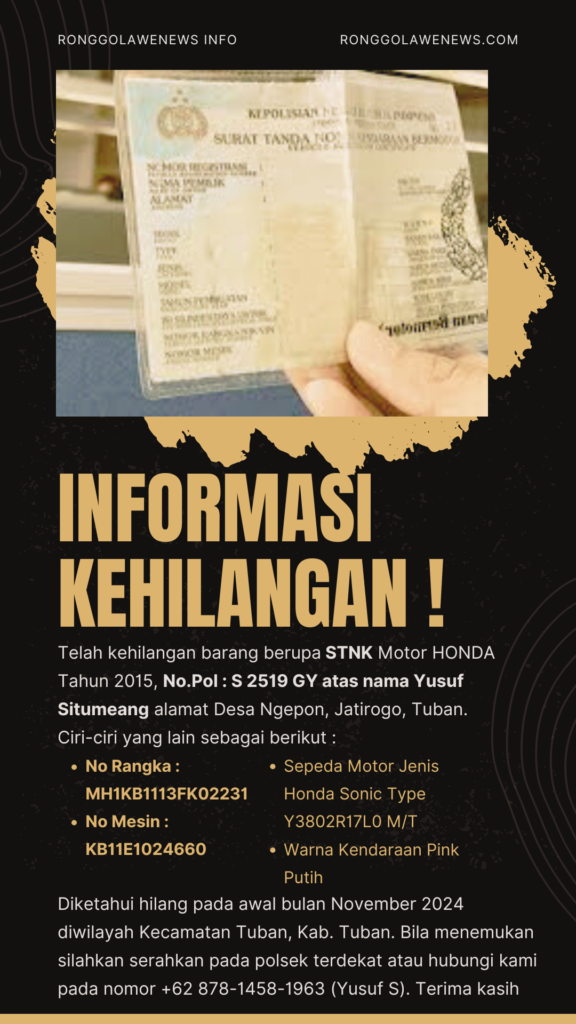Opini | Ronggolawe News
Setahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, negara patut mencatatnya sebagai langkah berani dalam sejarah kebijakan sosial. Jutaan anak kini menikmati akses pangan bergizi, lapangan kerja tercipta, dan komitmen negara terhadap pembangunan manusia tampak nyata. Namun di balik capaian itu, ada fakta yang jarang dibicarakan secara jujur: risiko terbesar justru menumpuk di titik paling bawah, pada dapur dan rantai pasok pangan.
Selama ini, perdebatan publik tentang MBG terlalu terpesona oleh angka—anggaran triliunan rupiah, jutaan penerima manfaat, ribuan sekolah. Padahal, keberlanjutan program tidak ditentukan oleh statistik makro, melainkan oleh kemampuan negara menjaga sistem yang bekerja setiap hari tanpa henti: dapur dan pasokan bahan pangan.
Dapur MBG adalah wajah paling konkret dari kehadiran negara. Di sanalah kebijakan bertemu realitas. Sepiring nasi yang terlambat, telur yang kualitasnya buruk, atau ayam yang tidak segar, langsung diterjemahkan publik sebagai kegagalan program. Ironisnya, kegagalan itu sering kali bukan hasil kelalaian dapur, melainkan akibat rapuhnya sistem pasok di hulu.
Dalam praktiknya, dapur MBG diposisikan sebagai penyangga guncangan.
Ketika harga telur melonjak atau distribusi tersendat, dapur dipaksa beradaptasi dengan margin yang semakin tipis dan risiko yang makin besar. Saat terjadi masalah kualitas, dapur pula yang pertama disorot, diperiksa, bahkan dikriminalisasi. Desain kebijakan semacam ini menempatkan aktor hilir sebagai kambing hitam sistemik.
Padahal, dapur bukan sekadar unit teknis. Ia adalah simpul sosial-ekonomi. Dapur menyerap tenaga kerja lokal, menghidupkan UMKM, dan memutar ekonomi desa maupun kota kecil. Ketika dapur goyah, dampaknya merembet ke buruh harian, pedagang kecil, hingga petani dan peternak sekitar.
Tekanan serupa terjadi pada rantai pasok. Lonjakan permintaan MBG bukan variabel netral. Ia menciptakan kejutan permintaan (demand shock) pada sistem pangan yang elastisitasnya rendah. Akibatnya, harga telur dan ayam terdorong naik, pasokan antarwilayah timpang, dan pasar lokal terganggu. Dalam struktur seperti ini, pemasok kecil yang tak sanggup memenuhi volume besar atau standar administratif berisiko tersingkir.
Masalahnya bukan pada niat MBG, melainkan pada tata kelolanya. Pengadaan berskala nasional yang terlalu terpusat cenderung memutus mata rantai lokal. Traceability lemah, akuntabilitas kabur, dan risiko kembali dilimpahkan ke dapur. Negara hadir sebagai pembeli besar, tetapi belum sepenuhnya hadir sebagai pengelola risiko.
Jika pola ini dibiarkan, MBG berpotensi menjadi paradoks: program gizi yang justru melemahkan ketahanan pangan lokal. Ini alarm serius. Program sebesar MBG tidak boleh berjalan dengan logika sektoral, apalagi membiarkan aktor paling lemah memikul beban paling berat.
Solusinya menuntut keberanian kebijakan. Negara harus mengakui dapur sebagai mitra strategis, bukan sekadar operator. Kepastian kontrak, perlindungan hukum, pembagian risiko yang adil, serta pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan harus menjadi standar nasional.
Di saat yang sama, rantai pasok harus ditata ulang. Desentralisasi pengadaan, prioritas pemasok lokal, koperasi, dan rantai pendek akan memperkuat keterlacakan sekaligus menstabilkan pasar daerah.
Transparansi data kebutuhan, stok, dan harga mutlak diperlukan agar pasar tidak terus bereaksi secara liar.
Setahun MBG seharusnya menjadi momen refleksi. Keberhasilan program gizi tidak diukur dari seberapa besar anggaran dibelanjakan, melainkan dari seberapa adil negara membagi risiko dan tanggung jawab. Dapur dan rantai pasok bukan beban, melainkan fondasi.
Jika negara mampu memperkuat keduanya sebagai satu ekosistem, MBG bukan hanya memberi makan hari ini, tetapi menjadi mesin transformasi sistem pangan nasional. Di situlah investasi sejati bagi generasi Indonesia ke depan diletakkan—bukan pada angka, melainkan pada tata kelola yang adil dan berkelanjutan.