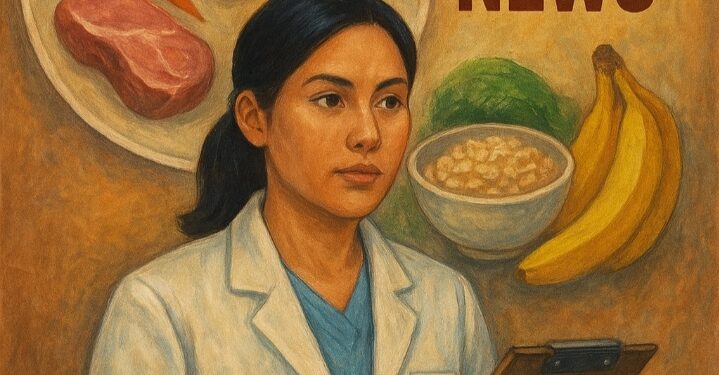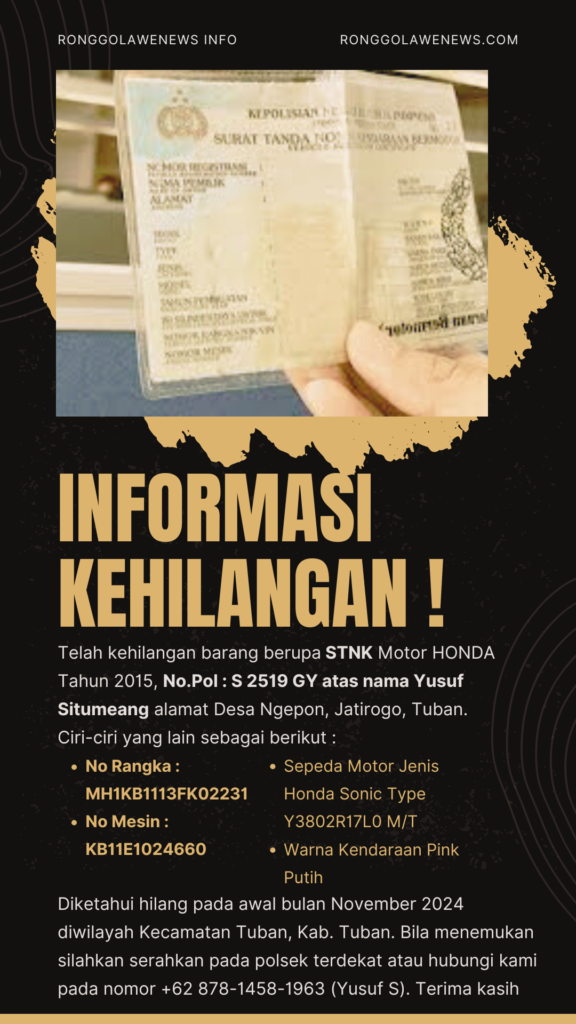Ketika Nyawa Publik Dipertaruhkan oleh Ide Kompromi dan Pelatihan Tiga Bulan
Jakarta, Ronggolawe News — Proyek pangan terbesar Indonesia dalam dua dekade terakhir, Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali memicu polemik keras. Bukan soal anggaran, bukan soal bahan pangan, melainkan dilema paling fundamental: apakah proyek sebesar ini bisa berjalan tanpa ahli gizi?
Pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menyebut bahwa lulusan SMA pun bisa menjadi pengawas gizi setelah pelatihan singkat tiga bulan, meledak seperti petasan di tungku minyak panas. Videonya viral, kritik mengalir deras, dan permintaan maaf pun meluncur—namun polemik sudah terlanjur terbakar.
Krisis Tenaga Ahli atau Krisis Nalar?
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui persoalan yang sebenarnya sederhana namun pelik: Indonesia kekurangan ahli gizi untuk mengawasi 30 ribu dapur MBG di seluruh daerah.
Lalu muncullah ide kompromi: membuka pintu bagi lulusan sarjana nongizi—bahkan yang tak pernah mempelajari metabolisme tubuh manusia—untuk duduk di kursi pengawas gizi setelah mengikuti pelatihan singkat. Surat edarannya disebut “sedang dipersiapkan”, namun tak pernah dipublikasikan.
Pertanyaan publik pun menggelayut:
Apakah “belum diumumkan” berarti belum ada, masih dibahas, atau justru sedang dicari-cari di laci yang salah?
Ahli Gizi: Profesi, Bukan Tambal Sulam
Ahli gizi Tan Shot Yen menegaskan bahwa ini bukan sekadar urusan menakar kalori seperti menghitung uang kembalian di warung.
“Mengawasi gizi bukan hitung-hitungan angka saja. Ini menyangkut nyawa manusia dengan kebutuhan gizi berbeda. Tidak bisa dipelajari dalam tiga bulan.”
Mengapa?
Karena pengawas gizi MBG harus mampu memetakan kondisi beragam:
siswa obesitas,
remaja wasting,
balita anemia,
ibu hamil kekurangan energi.
Semua membutuhkan intervensi berbeda.
Dan empat tahun pendidikan ahli gizi tidak bisa digantikan oleh kursus kilat.
Proyek Besar dengan Pondasi Rapuh
MBG adalah proyek raksasa dengan dana triliunan, ambisi dapur berbasis pangan lokal, dan harapan menghapus masalah gizi nasional. Namun:
sistem belum siap,
tenaga ahli kurang,
dan negara seperti terburu-buru membangun bangunan 30 lantai dengan pondasi bambu.
Di negara lain, profesionalisasi ahli gizi ditempa selama puluhan tahun. Indonesia baru menempatkan ahli gizi di panggung utama tahun ini—langsung panggung ukuran stadion.
Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Salah?
Bayangkan suatu pagi, di dapur umum di Cirebon, Bantaeng, atau Lampung Barat, seorang pengawas gizi—entah lulusan empat tahun atau tiga bulan—harus menakar protein ikan tongkol, menentukan menu untuk siswa anemia, dan memastikan ribuan anak menerima makanan yang aman dan layak.
Pertanyaannya menjadi:
Siapa yang kelak bertanggung jawab bila terjadi keracunan massal?
Negara? Pelatih tiga bulan? Atau anak-anak yang dijadikan percobaan?
Kesimpulan Kata Redaksi
Polemik MBG bukan soal elitis atau tidaknya profesi ahli gizi.
Ini soal keselamatan publik, akurasi ilmu, dan tanggung jawab negara.
Karena pada akhirnya, bangsa ini sudah terlalu sering melihat proyek besar jatuh karena pondasi yang sengaja dibuat rapuh.
Apakah kita akan mengulang kesalahan, atau memilih berdiri di atas keahlian, bukan improvisasi?
Bisakah Tenaga Non Profesional Menggantikan Ahli Gizi MBG?
Ketika Proyek Raksasa Dipertaruhkan pada Pelatihan Kilat dan Keberanian Spekulatif Negara
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan di ratusan daerah memunculkan pertanyaan paling krusial: Apakah tenaga non profesional benar-benar bisa menggantikan peran ahli gizi di lapangan?
Pertanyaan ini bukan sekadar debat akademik.
Ini menyangkut keselamatan jutaan anak sekolah, ibu hamil, balita, dan remaja yang menjadi penerima manfaat MBG.
Ledakan Polemik dari Senayan
Pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal yang menyebut lulusan SMA bisa menjadi pengawas gizi setelah pelatihan tiga bulan, langsung memicu badai kritik publik. Pernyataan itu kemudian diklarifikasi dan diikuti permintaan maaf, namun polemik keburu membesar.
Kata para pengamat, pernyataan tersebut mencerminkan cara berpikir proyek dulu, kapasitas belakangan — penyakit lama yang belum juga sembuh.
Dalih Negara: Kurang Tenaga Ahli
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui fakta pahit:
Indonesia kekurangan ahli gizi untuk mengawasi dapur MBG yang jumlahnya mencapai 30 ribu titik.
Karena itu, muncul ide kompromi: memperbolehkan lulusan sarjana bidang non gizi, bahkan lulusan SMA, menjadi pengawas gizi setelah mengikuti pelatihan singkat.
Namun, hingga kini:
Surat edaran resminya belum dipublikasikan, dan
kriterianya masih samar.
Pertanyaan publik pun menggantung:
Apakah ini solusi atau hanya jalan pintas yang berbahaya?
Ahli Gizi Tak Bisa Disulap dalam 3 Bulan
Ahli gizi Tan Shot Yen menolak keras gagasan substitusi pelatihan kilat.
“Mengawasi gizi tidak sesederhana menghitung kalori. Tiap individu punya kebutuhan biologis berbeda. Itu tidak bisa dipelajari dalam tiga bulan.”
Dalam praktik MBG, pengawas gizi harus mampu:
Menganalisis gizi anak obesitas maupun wasting,
Menangani remaja anemia,
Menentukan kebutuhan ibu hamil kekurangan energi,
Menghitung komposisi mikronutrien dan protein hewani berbasis pangan lokal.
Satu kesalahan tidak hanya menurunkan kualitas menu, tetapi
dapat menyebabkan keracunan massal, gagal tumbuh, dan masalah kesehatan jangka panjang.
Jika itu terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab?
Instruktur pelatihan kilat? Dinas daerah? Atau korban yang tidak mengerti apa-apa?
Pondasi Rapuh di Atas Dana Triliunan
Program MBG berdiri di atas ambisi besar, namun tanpa kesiapan tenaga ahli yang memadai.
Indonesia baru menempatkan ahli gizi sebagai ujung tombak tahun ini — langsung di skala nasional, bukan pilot proyek.
Dari pengalaman global, profesionalisasi gizi butuh:
Dekade pendidikan dan sertifikasi,
Sistem mutu dan regulasi ketat,
Standarisasi penanganan kasus klinis.
Namun Indonesia memilih strategi bangun kapal sambil berlayar, dan berharap badai tidak datang.
Kesimpulan Tajam Redaksi
Jadi, bisakah tenaga non profesional menggantikan ahli gizi?
Jawaban paling jujur, paling telanjang, dan paling logis adalah:
Bisa—jika bangsa ini siap menjadikan jutaan anak sebagai kelinci percobaan.
Tidak bisa—jika kita masih punya etika, akal sehat, dan rasa tanggung jawab publik.
Karena persoalan ini bukan tentang gengsi profesi,
melainkan tentang hak hidup sehat, keselamatan generasi, dan kredibilitas negara dalam mengelola uang rakyat.
Redaksi Investigasi – Media Ronggolawe News
Tajam, berani, dan berbeda.