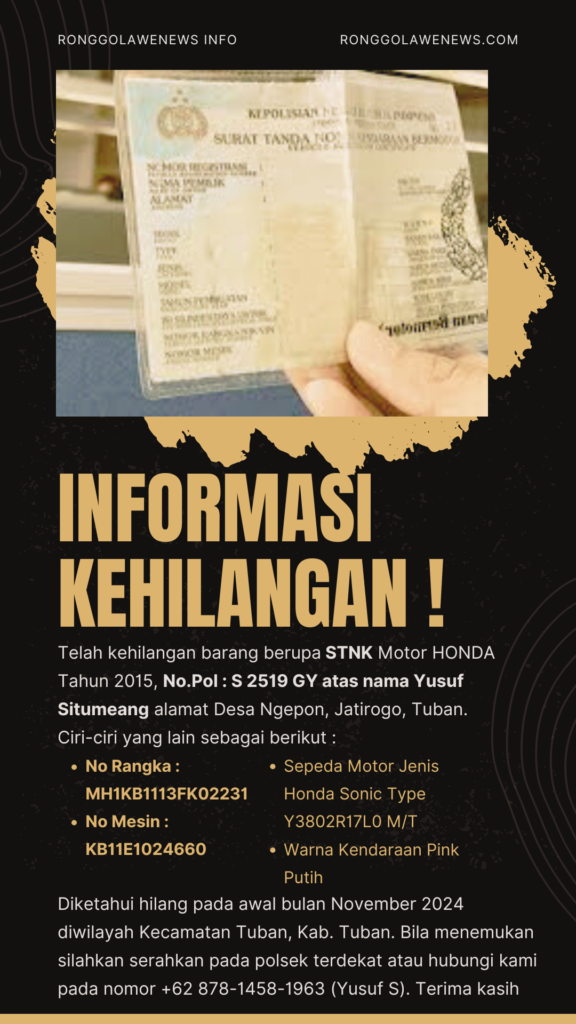Di awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto memilih sebuah jalan yang tidak mudah: berani bicara tentang realita paling getir bangsa ini. Ia mengakui bahwa masih banyak anak Indonesia yang berangkat sekolah tanpa sarapan, banyak keluarga yang hidupnya belum layak, dan terlalu banyak rakyat yang bahkan tidak menikmati hasil kemerdekaan sepenuhnya.
Dari kesadaran itulah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir. Sebuah gagasan lama yang dibangun dari keresahan mendalam, bahkan jauh sebelum beliau duduk di kursi presiden. Dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, Prabowo mempertanyakan hal yang seharusnya membuat kita malu sebagai bangsa: mengapa negeri yang kaya raya ini tidak mampu menjamin rakyatnya cukup makan?
Pertanyaan itu bukan sekadar teks dalam buku, tetapi suara nurani.
Namun hampir sebelas bulan berjalan, nurani itu kini sedang diuji.
Fakta-fakta di lapangan menunjukkan paradoks yang lain. Kasus keracunan makanan berulang. Dapur yang tidak memenuhi standar. Pengawasan yang longgar. Dan—yang paling menohok—isu soal tata kelola keuangan yang tidak sesederhana laporan kertas.
Saya sudah menuliskan peringatan itu sebelumnya dalam artikel “Reformasi BGN: Mencegah MBG Jadi Beban Sosial dan Fiskal”. Dan hari ini, kekhawatiran itu justru makin nyata.
Kita sedang menyaksikan sebuah cita-cita besar yang terguncang oleh kekacauan teknis, miskinnya koordinasi, hingga perilaku sebagian oknum yang memandang MBG tidak lebih dari proyek besar dengan anggaran besar.
Lalu muncullah pernyataan Wakil Ketua DPR. Dan api kecil berubah jadi bara.
Ucapan Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Forum SPPG di Bandung—bahwa “MBG tidak memerlukan ahli gizi”—bukan hanya keliru, tetapi mencederai akal sehat bangsa ini.
Dan ketika ia menyebut cukup “memegang palu” untuk menyelesaikan semuanya, kita melihat masalah lain: mentalitas politik yang merasa bisa mengatur gizi anak bangsa dengan sentimen dan emosi.
Ia memang sudah meminta maaf. Tetapi dampak sosial dari ucapannya tersisa.
Ahli gizi tersakiti. Akademisi kecewa. Publik geram. Dan saya percaya, siapa pun yang mencintai republik ini pasti akan geleng kepala.
Karena kebenarannya sederhana: MBG tidak mungkin berdiri tanpa ilmu gizi.
Setiap gram makanan, setiap prosedur sanitasi, setiap standar menu—semuanya dijaga oleh keilmuan. Tanpa ahli gizi, MBG hanya akan menjadi program seremonial penghabisan anggaran. Lebih buruk lagi, bisa menjadi ancaman kesehatan bagi jutaan anak.
Ahli gizi bukan pelengkap.
Mereka adalah fondasi.
Mereka adalah benteng kualitas.
Menghapus mereka sama seperti membuang rem pada kendaraan yang sedang menuruni bukit.
Saya percaya Presiden Prabowo punya visi besar. Namun visi besar tetap bisa runtuh oleh pelaksanaan yang buruk.
MBG bukan proyek politik yang cukup diselesaikan dengan pidato. Ia membutuhkan:
tata kelola yang rapi,
pengawasan yang keras,
standar yang ketat,
dan terutama: penghargaan terhadap profesi yang menyelamatkan masa depan anak bangsa.
Dan jangan lupa, anggaran ratusan triliun adalah medan yang sangat menggoda. Jika BGN tidak memperkuat regulasi teknokratik sejak awal, MBG bisa berubah dari investasi peradaban menjadi beban sosial dan fiskal yang kelak ditinggalkan sebagai catatan buruk sejarah.
Pada akhirnya, ini soal masa depan bangsa.
Bangsa yang besar tidak diukur dari megahnya proyek pemerintah, tetapi dari apakah anak-anaknya makan dengan layak.
Dan ketika kita bicara soal makan, kita bicara soal gizi.
Ketika bicara soal gizi, kita bicara soal profesional.
Dan ketika bicara soal profesional, tidak ada ruang untuk arogansi atau pengabaian.
Presiden sudah menyalakan obor besar bernama MBG.
Jangan biarkan obor itu redup hanya karena ulah orang-orang yang tidak memahami makna amanah.