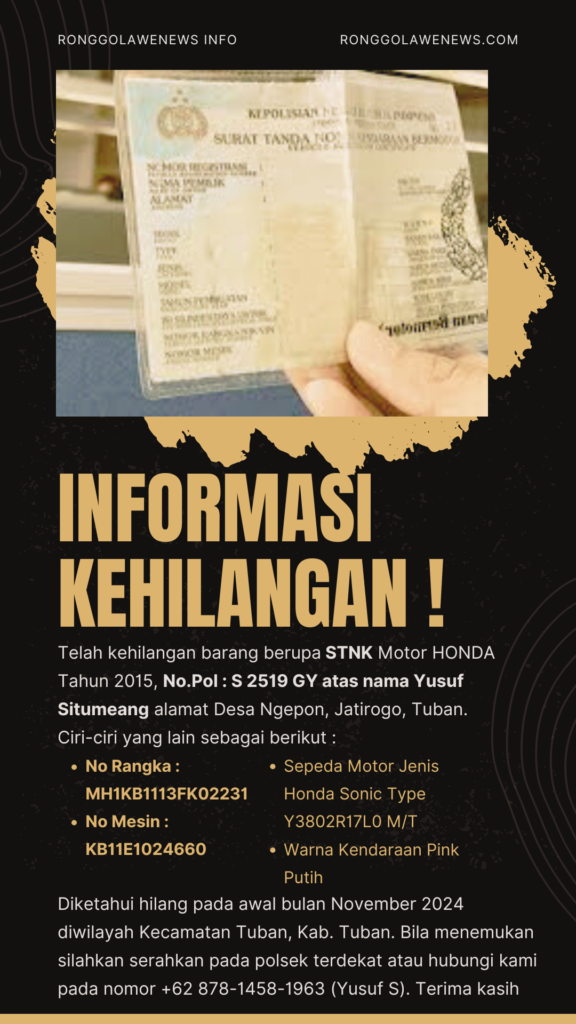Oleh: Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)
Kerusuhan 1998 versus kerusuhan era serba canggih.
Mari kita membandingkan pengelolaan unjuk rasa era 1998 saat tanpa teknologi canggih dengan era sekarang yakni masa dengan penuh teknologi canggih namun tidak optimal.
Minimnya teknologi pengawasan pada 1998 karena alat pengawasan yang digunakan sangat terbatas, hanya mengandalkan intelijen konvensional seperti informan dan pengamatan fisik. Tidak ada spyware canggih yang dapat memantau komunikasi digital dalam kerangka unjuk rasa secara real-time.
Dampak ketiadaan teknologi menyebabkan aparat kesulitan mendeteksi provokator atau mengantisipasi kerusuhan. Kerusuhan Mei 1998 mengakibatkan 1.200 korban jiwa, perusakan 2.500 bangunan, dan kerugian ekonomi mencapai Rp 2,5 triliun. Sekelompok orang menggunakan isu etnis sebagai kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari krisis ekonomi. Tanpa alat deteksi dini, narasi isu itu menyebar cepat dan memicu kekerasan massal.
Era 2017-2025 ketersediaan teknologi oleh pemerintah namun gagal implementasi
Dari 2017 hingga 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkali-kali menyalakan alarm soal pengadaan peralatan intelijen di berbagai instansi negara. Temuan-temuan ini menunjukkan pola yang berulang: anggaran besar, istilah pengadaan yang samar, dan minim transparansi. Berikut uraiannya:
Tahun 2017, Kepolisian RI dan Kementerian Pertahanan pada IHPS I 2017 No. 56/LHP/XVI/05/2017, BPK menemukan 8.323 kasus ketidakpatuhan senilai Rp30,87 triliun di 86 kementerian/lembaga. Salah satunya pengadaan “peralatan khusus” dan “komunikasi taktis” yang tanpa spesifikasi jelas. Istilah samar ini diduga menjadi celah untuk menyembunyikan pengadaan spyware atau perangkat pengawasan canggih lainnya.
Pada tahun 2018, Kepolisian RI di LHP Polri 2018 No. 44/LHP/XIV/05/2018, audit BPK mencatat pengadaan intelijen senilai Rp685 miliar yang dilakukan tanpa tender terbuka. Investigasi ICW melalui Opentender.net mengungkap proyek Zero-Click Intrusion System senilai Rp149 miliar yang dimenangkan PT Radika Karya Utama. Alat ini memiliki kapabilitas mirip Pegasus, meskipun Polri membantah membeli produk NSO Group secara langsung.
Di tahun 2019, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada LHP BSSN 2019 No. 20/LHP/XVIII/04/2019 BPK menemukan Rp420 miliar belanja infrastruktur siber dengan realisasi rendah, output tak terbukti, dan perencanaan lemah. Ini jadi contoh klasik belanja “lubang hitam”: uang besar keluar, hasilnya nihil.
Tahun 2020, Polri, Kementerian Pertahanan, BSSN di IHPS I 2020 No. 24/LHP/XVIII/06/2020 audit semester pertama tahun 2020 mencatat Rp19,40 triliun belanja modal bermasalah di 87 K/L. Polanya seragam: penunjukan langsung, spesifikasi samar, dan output tak terukur. Inilah tahun ketika istilah “peralatan taktis” atau “sistem intelijen” menjadi payung sempurna untuk menyamarkan spyware.
Di 2021, Badan Intelijen Negara pada LHP BIN 2021 No. 13/LHP/XVIII/02/2021, BIN menganggarkan lebih dari Rp1 triliun untuk alat intelijen digital, tapi audit BPK hanya menyentuh aspek administrasi. Pengadaan substansial ditutup rapat dengan alasan “rahasia negara,” menjadikan BIN kotak hitam belanja teknologi.
2022, Polri dan Kementerian Pertahanan terlihat di LHP Polri 2022 No. 15/LHP/XVIII/02/2022, audit BPK menunjukkan pembelian perangkat pengawasan senilai sekitar Rp1,1 triliun. Lagi-lagi prosesnya penunjukan langsung tanpa analisis kebutuhan memadai, membuka peluang mark-up besar-besaran.
Dan tahun 2023 BSSN di LHP BSSN 2023 No. 20/LHP/XVIII.BDG/03/2023, belanja Rp310 miliar untuk deteksi ancaman digital menghasilkan laporan nihil. Temuan BPK menyoroti output tak terukur, integrasi lemah, dan laporan pemanfaatan tidak ada.
Serta tahun 2024–2025 Kejaksaan Agung berdasar data LPSE dan investigasi TTI menemukan total belanja intelijen mencapai Rp5,78 triliun.
Investigasi Transparansi Tender Indonesia itu temukan tender-tender formalitas, termasuk proyek Rp300 miliar dengan selisih harga hanya Rp20 juta dari pagu. Peraturan Jaksa Agung No.1/2025 bahkan menghalalkan ketertutupan proses pengadaan, menjadikan pola ini skandal terbesar pengadaan intelijen pascareformasi. Ini tentu memiliki dampak buruk.
Presiden Prabowo ‘terimbas buruk’ kerusuhan Agustus 2025
Beberapa laporan menyebut 7 orang meninggal dunia akibat rangkaian demonstrasi antara tanggal 25–31 Agustus 2025. Ada pula laporan lain yang menyebut 8 orang tewas hingga tanggal 1 September 2025. Sementara itu, versi berbahasa Inggris menyebutkan 6 orang tewas, dengan minimal 5 orang luka-luka, termasuk Affan Kurniawan dan beberapa korban kebakaran gedung DPRD Makassar.
Ringkasnya, korban tewas kisaran 6–8 orang, luka-luka diketahui ada minimal 5, kemungkinan di lapangan lebih banyak. Penahanan sekitar 2.000 orang diamankan. Kerusakan fisik dan infrastruktur sebanyak 37 gedung DPRD di berbagai daerah telah dibakar atau mengalami kerusakan parah. Kerusakan infrastruktur lebih luas, seperti halte TransJakarta terbakar, layanan bus dan MRT terganggu, dikabarkan digratiskan selama satu minggu. Fasilitas tol rusak, serta gedung bersejarah maupun infrastruktur transportasi mengalami vandalisme dan pembakaran .
Estimasi kerugian harta benda hingga kini belum ada yang resmi menyatakan angka total kerugian finansial akibat kerusuhan itu. Namun, luasnya kerusakan, termasuk gedung-gedung pemerintahan, transportasi publik, dan properti komersial, menunjukkan bahwa kerugian bisa sangat besar.
Di saat negara kita sudah punya gawai kelas premium yakni spyware, lawful intercept, dan sistem intelijen digital, ironinya, saat massa pengunjuk rasa turun ke jalan, alat mahal itu justru tidak bisa hadir sebagai penjaga nyawa rakyat dari perilaku jahat provokator. Alat-alat itu nyaris tak terlihat fungsinya! Mengapa hal itu terjadi? Apakah Presiden Prabowo Subianto mumpuni mencermati hal itu?
Masalahnya terletak pada tata cara membeli, memahami, dan mengoperasikan, itu bukan semata pada teknologinya. Intinya terlihat dari pola temuan BPK yang bersifat konsisten, yakni pengadaannya kerap memakai istilah samar, dilakukan dengan penunjukan langsung, outputnya tak terukur, dan itu semua yang akhirnya merongrong akuntabilitas!
Teknologi yang lazim dipakai intel itu apa sih?
- Spyware adalah perangkat lunak pengintai kelas premium, misal Pegasus dari NSO Group, Predator dari Intellexa, Candiru, yang bisa masuk ke ponsel/komputer tanpa klik dan bisa mengambil data, mikrofon, kamera, lokasi.
- Lawful intercept yaitu penyadapan berdasarkan perintah pengadilan dengan jejak audit ketat, dan setiap akses harus bisa ditelusuri.
- Sistem intelijen digital terintegrasi adalah “ruang komando” yang memadukan server kendali, big data analitik, pengenal wajah, pelacak lokasi, dan pemeta situasi real-time.
Filosofi awalnya, seluruh alat itu untuk melindungi rakyat dan demokrasi, bukan malah untuk membungkam kritik. Penggunaannya gagal bukan pada alat, tapi pada proses pengadaan dan pemanfaatan.
Kenapa alat secanggih itu gagal melindungi pendemo dari provokator?
Pertama, pengadaannya kacau dan fungsinya kabur. Di atas kertas tertulis pengadaan “peralatan khusus” dan “sistem intelijen”, tapi spesifikasinya disamarkan. Vendornya dipilih lewat penunjukan langsung, sehingga kompetisi harga hilang. Hasilnya klasik, yaitu mahal tapi salah spesifikasi. Begitu tiba di lapangan, alat tidak kompatibel dengan jaringan yang ada, tidak pernah di-commissioning (uji terima fungsi), bahkan ada yang hanya jadi “pajangan mahal” di rak kantor. Bukan karena teknologinya buruk, melainkan karena cara membelinya yang asal-asalan.
Kedua pimpinan tidak paham dan operator tidak siap. Teknologi intelijen itu bukan “colok langsung beres”. Ia butuh doktrin operasi, SOP integrasi, uji fungsi berkala, dan latihan gabungan lintas instansi. Tanpa itu, “ruang komando” tak pernah benar-benar menyala saat tensi memuncak. Di titik kritis, data tak mengalir, kamera tak sinkron, peta risiko tidak terbarui. Aparat di lapangan bergerak seperti tanpa kompas, padahal kompasnya ada, hanya tidak pernah diajarkan cara membacanya.
Ketiga, audit negara minim substansi teknis. Audit resmi kita kuat pada kepatuhan keuangan, apakah kontraknya ada, kuitansinya lengkap. Tapi saat menyentuh substansi teknologi, temboknya tinggi. Tanpa forensik digital, auditor sulit untuk memastikan server yang dibeli berisi sistem kelas dunia atau sekadar rak kosong berlabel premium. Inilah celah di mana salah-beli dan salah-guna bisa bersembunyi rapi di balik dokumen yang tampak resmi.
Keempat,“rahasia” dijadikan tameng. Kerahasiaan memang perlu untuk melindungi taktik dan keselamatan, tetapi itu bukan untuk menghapus akuntabilitas. Ketika semua disapu ke kotak “rahasia”, maka pengawasan substantif terhenti. Publik tak tahu apa yang dibeli, wakil rakyat tak bisa menilai faedahnya, auditor hanya boleh melihat kulit administrasi.
“Rahasia” pun berubah menjadi lubang hitam yang menelan uang negara, menelan kepercayaan, dan pada akhirnya menelan kesempatan menyelamatkan nyawa rakyat!
Intinya, teknologi ini bisa, dan seharusnya menjadi penjaga demokrasi. Tapi tanpa pengadaan yang bersih, kepemimpinan yang paham fungsi, operator yang terlatih, audit yang menyentuh jantung teknologinya, dan kerahasiaan yang diawasi, maka alat secanggih apa pun hanya akan menjadi senjata makan tuan!
Analisis hukum
Presiden Prabowo Subianto sudah saatnya untuk membenahi tatakelola peralatan teknologi pemerintah utamanya yang berfungsi dalam kaitan kerja-kerja keintelijenan. Supaya maksimalisasinya bisa menyelamatkan negara dan rakyat.
Jangan seperti kerusuhan kemarin yang akhirnya membuat buruk kinerja dan performa pemerintahan Prabowo di mata dalam dan luar negeri.
Regulasi terkait tatakelola itu yang perlu dibenahi adalah:
- Undang-Undang 15/2006 memberi kewenangan luas kepada auditor negara, tetapi akses ke substansi sering dibatasi oleh klasifikasi “rahasia negara”.
- Peraturan Presiden 16/2018 (PBJ) membuka ruang penunjukan langsung untuk kondisi tertentu, sehingga celah ini perlu pengaman akuntabilitas.
- Undang-Undang 14/2008 (KIP) dan Undang-Undang 27/2022 (PDP): menuntut transparansi dan proporsionalitas.
- Peraturan Jaksa Agung No. 1/2025 dan Peraturan BSSN No. 12/2024 mengatur “pengadaan rahasia”; harus diseimbangkan dengan mekanisme audit substantif agar tak jadi selimut impunitas.
Resep perbaikan dari alat mahal jadi penjaga demokrasi
Selama ini publik cuma mendengar jargon “digitalisasi keamanan” atau “penguatan intelijen”. Faktanya? Uang rakyat habis triliunan, tapi korban unjuk rasa masih berjatuhan. Kalau negara serius mau mengubah situasi ini, resepnya jelas, bukan slogan, yakni:
- Audit kedaulatan digital dengan memeriksa nyawa teknologi, bukan kertas kontrak. BPK harus turun tangan bukan hanya memeriksa kuitansi. Bentuk Satgas Audit Substantif yang berisi auditor negara plus ahli forensik digital independen. Mandatnya jelas untuk menguji fungsi perangkat, menelusuri asal-usulnya sampai broker lintas negara, dan memastikan perangkat lulus uji kinerja.
Pengadaan yang katanya “rahasia” tetap bisa diaudit, dimana prosesnya dilakukan di ruang aman, tanpa membocorkan taktik, tapi hasil ringkasannya wajib dipublikasikan untuk rakyat.
- Transparansi teknis yang aman dimana publik berhak tahu faedahnya. Judul paket pengadaan tidak boleh lagi “peralatan khusus”, harus spesifik, jelas fungsinya. Sertakan standar performa dan interoperabilitas supaya tidak ada lagi alasan “tidak kompatibel”.
Ringkasan hasil uji penerimaan yang tanpa rincian sensitif harus diumumkan. Fitur intrusif seperti penyadapan wajib memiliki log aktivitas yang diaudit secara berkala oleh otoritas yudisial.
- Doktrin operasi teknologi terkait unjuk rasa adalah untuk menjaga pengunjuk rasa dari hal-hal buruk bukan untuk membungkam. Bangun pusat komando terpadu dengan peta kerumunan real-time, deteksi provokasi, dan toolkit de-eskalasi.
Targetnya sederhana, yakni minimalkan bentrok, maksimalkan pencegahan dini. Semua alat harus diuji lewat latihan gabungan lintas lembaga sebelum dinyatakan operasional. Operator wajib disertifikasi, agar teknologi mahal ini tidak lagi jadi “pajangan”.
- Regulasi diperbarui, celah ditutup, batasi penunjukan langsung untuk pengadaan teknologi sensitif. Wajib ada pembanding teknis independen supaya tidak ada mark-up liar. Aturan “rahasia negara” harus disinkronkan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Perlindungan Data Pribadi, dimana rahasia boleh, namun impunitas tidak boleh.
- Libatkan publik, bangun kepercayaan dengan memberi akses terbatas bagi komunitas pemerhati, dan lembaga pemantau lain untuk mengaudit pola belanja dan uji fungsi, yakni versi tersensor. Buat jalur pengaduan teknis yang jelas, sehingga ketika ada dugaan salah-beli atau salah-guna, ada SLA tindak lanjut yang mengikat.
Dengan langkah itu, uang rakyat yang triliunan rupiah tidak lagi menguap untuk alat yang tidak jelas fungsinya. Teknologi mahal bisa jadi penyelamat, bukan ancaman. Negara tidak perlu menunggu korban berikutnya untuk sadar bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci.
Inti yang perlu diingat oleh publik
- Teknologi pengawasan digital bisa menyelamatkan nyawa kalau dibeli dengan cara yang benar, diuji benar, dipakai benar, dan diawasi benar.
- Yang merusak demokrasi bukan alatnya, melainkan kerahasiaan tanpa akuntabilitas, pengadaan yang culas, dan kepemimpinan yang tak paham fungsi.
- Uang rakyat harus kembali ke tujuan awal yakni melindungi rakyat, termasuk saat unjuk rasa, bukan untuk membungkamnya.
“Uang rakyat seharusnya membiayai keamanan dan demokrasi, bukan membeli alat yang kemudian jadi membungkam suara rakyat!”