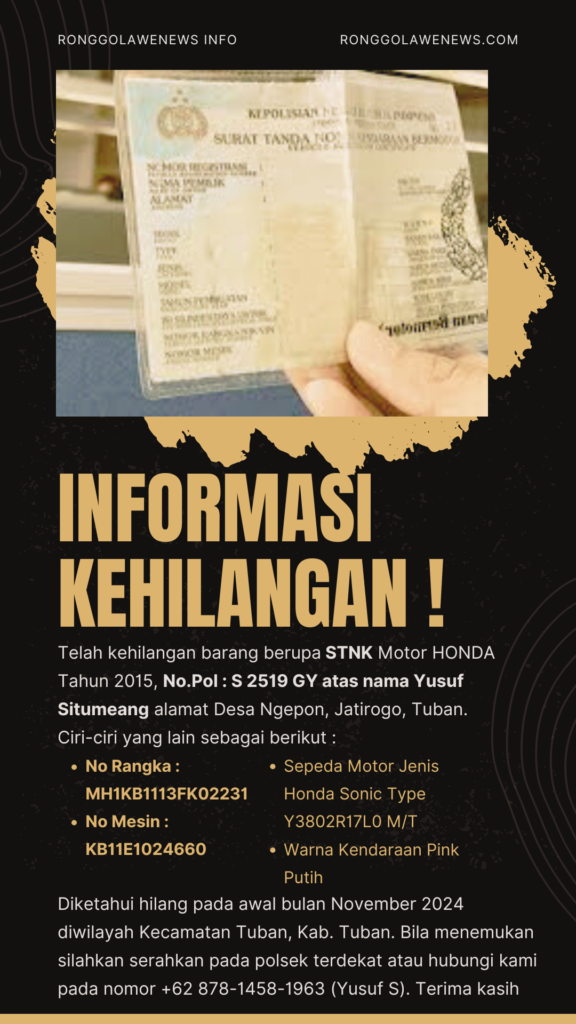Oleh: Anto Sutanto
Pemimpin Redaksi Media Ronggolawe News
Setiap kali rakyat turun ke jalan, selalu ada satu pola yang berulang: barisan aparat kepolisian berjejer di depan gedung DPR, seakan-akan mereka bukan pengayom masyarakat, melainkan tembok besi yang melindungi kursi-kursi empuk para wakil rakyat.
Padahal rakyat yang datang bukan untuk berhadapan dengan polisi, melainkan ingin ditemui, didengar, dan diberi jawaban oleh anggota DPR yang katanya mewakili mereka. Namun kenyataannya, DPR lebih sering bersembunyi di balik pagar kawat berduri dan tameng polisi, enggan keluar menatap mata rakyat yang mereka wakili.
Inilah yang membuat setiap demonstrasi sering berubah menjadi benturan. Bukan karena rakyat ingin rusuh, tetapi karena negara justru menjadikan polisi sebagai benteng politik. Polisi dipaksa menjadi “perisai kekuasaan” yang menanggung amarah rakyat, sementara DPR menikmati kenyamanan ruang rapat ber-AC tanpa harus menghadapi gelombang kekecewaan rakyat secara langsung.
Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis keamanan, tetapi masalah moral politik. DPR seharusnya menjadi ruang dialog rakyat, bukan benteng eksklusif yang hanya bisa diakses lewat izin dan protokol. Jika wakil rakyat benar-benar berani, mereka akan keluar menemui demonstran, berdialog, bahkan jika perlu berbeda pendapat secara terbuka di jalanan.
Ironisnya, ketika benturan terjadi, pemerintah sering menyalahkan “provokator” atau bahkan menyebut adanya “tunggangan asing”. Seakan-akan rakyat yang sudah muak dan menuntut keadilan dianggap tidak punya kesadaran sendiri. Inilah bentuk penghinaan paling nyata terhadap kedaulatan rakyat.
Pertanyaan mendasar: sampai kapan DPR terus berlindung di balik tameng aparat? Sampai kapan rakyat harus berhadapan dengan polisi, bukan dengan wakil yang mereka pilih sendiri?
Jika pola ini terus berulang, bukan hanya citra DPR yang hancur, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara. Dan ketika rakyat kehilangan kepercayaan, benteng sebesar apapun tak akan mampu menahan gelombang perubahan.
Ada beberapa faktor yang membuat demonstrasi sering berujung pada gesekan antara rakyat dan aparat kepolisian, meskipun tuntutan utama demonstran biasanya sederhana: ingin didengar dan ditemui wakil rakyat/DPR.
Beberapa sebab yang sering terjadi:
- Paradigma keamanan
Polisi di Indonesia lebih sering memandang demo sebagai potensi ancaman ketertiban umum, bukan sebagai hak demokratis rakyat. Akibatnya pendekatannya lebih ke represif daripada dialogis. - Kultur politik DPR
Banyak anggota DPR enggan turun langsung menemui massa, sehingga terjadi “kekosongan komunikasi”. Celah ini biasanya diisi polisi sebagai “tameng” DPR, sehingga rakyat merasa mereka dibenturkan. - Instruksi pengamanan
Aparat menjalankan SOP ketat untuk mencegah kerusuhan, tetapi sering kali over-acting, seperti membubarkan paksa atau menghalangi akses masuk, yang justru memicu kemarahan massa. - Kurangnya ruang dialog
Akses rakyat ke DPR atau pemerintah kadang diputus oleh birokrasi. Alih-alih menyiapkan jembatan komunikasi, negara justru menyiapkan barisan aparat. - Politik alibi
Pemerintah dan DPR kadang menggunakan aparat sebagai “perisai politik”, sehingga seolah benturan terjadi antara rakyat vs polisi, padahal substansi sebenarnya rakyat menuntut jawaban DPR.
Intinya, rakyat tidak pernah ingin berhadapan dengan polisi, tetapi ingin didengar DPR. Polisi sering ditempatkan sebagai pagar besi, dan ketika dialog tidak terbuka, benturan jadi sulit dihindari.
Bila Rakyat Sudah Muak: Menyalahkan Asing atau Menyalahkan Diri Sendiri?
Gelombang ketidakpuasan rakyat semakin nyata. Dari jalanan hingga ruang digital, suara-suara kritis rakyat menggema, menandakan satu hal: rakyat sudah muak. Mereka tidak lagi mampu menahan derita penindasan yang ironisnya justru datang dari bangsa sendiri—dari kebijakan yang menindas, dari aparat yang represif, hingga dari penguasa yang sibuk mempertahankan citra ketimbang mendengarkan jeritan masyarakat.
Namun, yang lebih menyakitkan adalah sikap pemerintah yang kerap mengalihkan isu. Alih-alih melakukan introspeksi, mereka dengan enteng menyalahkan “tunggangan pihak asing”. Narasi klasik yang seolah menjadi tameng suci untuk menutupi kebobrokan pengelolaan negeri ini.
Pertanyaannya sederhana: sampai kapan rakyat akan terus dituduh sebagai korban provokasi asing? Apakah pemerintah begitu buta hingga tidak mampu melihat bahwa sumber kemarahan rakyat berasal dari dalam negeri sendiri? Dari kebijakan yang tidak berpihak, dari kesenjangan yang semakin melebar, dan dari rasa keadilan yang semakin terkoyak.
Menuding asing adalah cara mudah untuk lari dari tanggung jawab. Tapi rakyat bukan lagi massa yang bisa dibohongi dengan jargon murahan. Mereka paham, yang menindas bukanlah bangsa asing, melainkan segelintir elite yang seharusnya melindungi mereka.
Bila rakyat sudah muak, kemarahan itu bukan lagi sekadar kritik. Itu adalah tanda alarm keras yang harus dijawab dengan perubahan nyata, bukan dengan kambing hitam. Sejarah membuktikan: saat penguasa menutup telinga, rakyat akan membuka jalan.
Indonesia tidak butuh alasan, Indonesia butuh keberanian untuk jujur.
Secara konstitusional, kedudukan DPR RI (pusat) dan DPRD (daerah) diatur dalam UUD 1945. Karena itu, tidak sembarang lembaga bisa membubarkannya. Berikut penjelasannya:
- DPR RI (Pusat)
DPR adalah lembaga negara yang dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu.
Tidak bisa dibubarkan oleh presiden, pemerintah, maupun lembaga lain.
Jika ada perubahan kedudukan, fungsi, atau bahkan pembubaran DPR, hal itu hanya bisa dilakukan lewat Amandemen UUD 1945 oleh MPR.
Artinya, satu-satunya cara membubarkan DPR adalah melalui perubahan konstitusi.
- DPRD (Daerah)
DPRD adalah lembaga legislatif daerah, juga dipilih lewat pemilu.
Sama halnya, tidak bisa dibubarkan oleh kepala daerah (bupati, wali kota, gubernur), presiden, atau menteri.
Bila ada masalah serius (misalnya anggota DPRD melakukan korupsi massal), yang bisa terjadi adalah pembekuan sementara aktivitas DPRD oleh Mendagri dengan dasar hukum yang jelas, bukan pembubaran permanen.
Untuk benar-benar menghapus DPRD, lagi-lagi hanya bisa lewat perubahan UU Pemerintahan Daerah dan konstitusi, karena DPRD merupakan amanat UUD 1945 Pasal 18.
- Kesimpulan
👉 Jadi, baik DPR maupun DPRD tidak bisa dibubarkan oleh presiden atau pemerintah.
👉 Pembubarannya hanya mungkin lewat perubahan UUD 1945 (untuk DPR) atau perubahan UU + UUD (untuk DPRD).
👉 Yang berwenang melakukan amandemen UUD adalah MPR (gabungan DPR dan DPD).
📌 Dengan kata lain: secara hukum, jalan satu-satunya membubarkan DPR/DPRD adalah lewat jalur konstitusi, bukan keputusan sepihak eksekutif.
Media Ronggolawe News: Suara Kebenaran, Suara Rakyat.
Puisi Kemarahan Rakyat
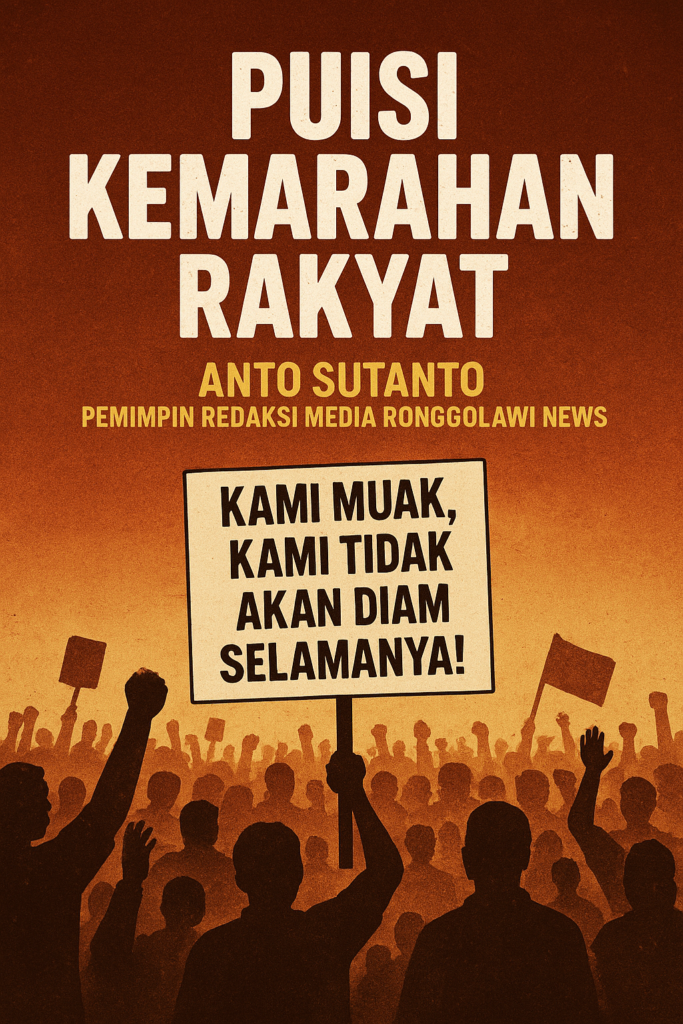
Oleh: Anto Sutanto
Pemimpin Redaksi Media Ronggolawe News
Di jalan-jalan berdebu, suara rakyat menggema,
teriakan bukan lagi bisikan, tapi gelegar dada.
Mereka turun bukan untuk hura-hura,
melainkan karena janji penguasa berubah jadi luka.
DPR yang mestinya rumah aspirasi,
menutup pintu, mengunci hati.
Polisi dijadikan tameng berdiri,
membenturkan saudara dengan saudari.
Apakah negeri ini milik segelintir kuasa?
Apakah rakyat hanya boneka di panggung sandiwara?
Kesabaran telah mencapai ujung tebing,
dan air mata berubah jadi bara yang kering.
Dari desa, kota, hingga pelosok negeri,
demonstrasi meletup, meluas tak terbendung lagi.
Rakyat bersatu dalam satu kata,
“Kami muak, kami tidak akan diam selamanya!”
Sejarah menulis dengan darah dan keberanian,
ketika keadilan dibungkam, rakyat jadi titian.
Dan bila penguasa terus berpura-pura,
maka badai rakyatlah yang jadi penentunya.