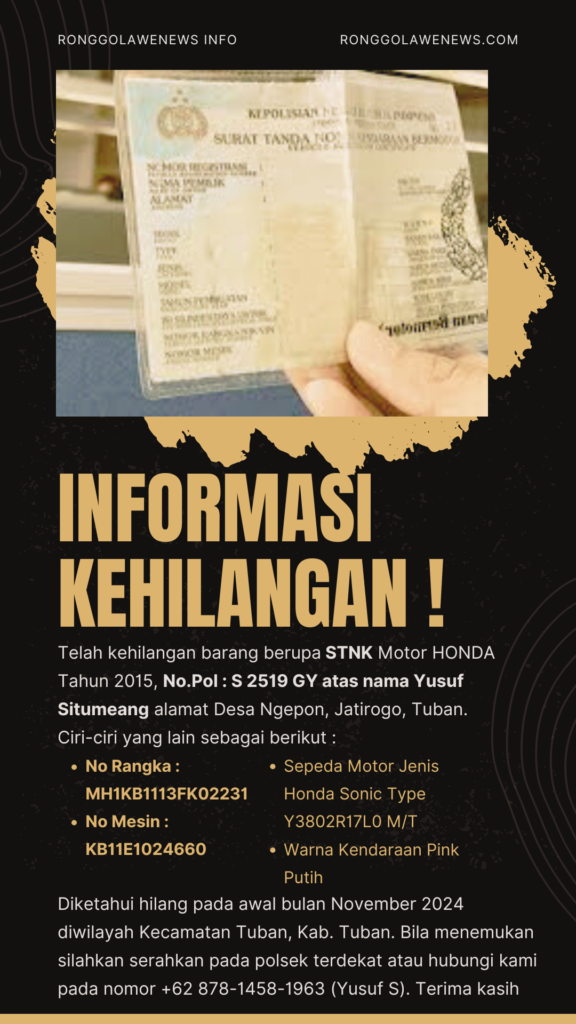Tuban,Ronggolawe News – Di tengah derasnya modernisasi dan ketatnya regulasi hukum positif, keris tetap berdiri sebagai simbol yang tak pernah kehilangan relevansi. Di banyak ruang kebudayaan Nusantara, ia bukan sekadar sebilah besi: ia adalah penanda identitas, martabat, dan spiritualitas. Namun dalam ruang hukum yang kaku dan formal, keris kerap dipaksa masuk ke dalam kategori “senjata penusuk”. Dua dunia ini—adat dan hukum—bertubrukan pada titik yang sama: Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
Keris sebagai pusaka hidup, dan keris sebagai objek hukum positif, seolah berada dalam dua alam yang berbeda. Di sinilah problematika itu bermula.

( Foto : Dok. Media Ronggolawe News)
Keris: Benda Pusaka yang Diatur Seperti Senjata
Dalam sejarahnya, keris memang pernah menjadi instrumen pertahanan dan serangan. Pada era antar kerajaan, ia digunakan untuk menegakkan kekuasaan, menolak ancaman, atau mengukuhkan kemenangan.
Tetapi konteks hari ini sudah berubah total. Keris telah berevolusi menjadi living heritage—warisan budaya takbenda yang diakui UNESCO sejak 2005. Ia dihormati dalam upacara adat, diwariskan sebagai pusaka keluarga, dan menjadi karya seni tosan aji yang memuat filsafat mendalam.
Namun di sisi lain, UU Darurat 12/1951—produk masa revolusi dan konsolidasi keamanan negara—menempatkan keris dalam rumpun senjata yang pembawaannya dapat dipidana hingga 10 tahun bila dilakukan “tanpa hak”.
Di sinilah letak paradoksnya:
Bagaimana bisa pusaka yang diakui UNESCO, Undang-Undang Kebudayaan, dan Undang-Undang Cagar Budaya… sekaligus dipersepsikan sebagai senjata tajam yang rawan dipidana?
Hukum Kebudayaan Memberi Legitimasi, Hukum Pidana Memberi Kecurigaan
Beberapa regulasi jelas memberikan ruang dan pengakuan:
UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan karya bernilai cipta-rasa-karsa sebagai bagian kebudayaan yang wajib dilindungi.
UU 11/2010 tentang Cagar Budaya secara tegas menyebut keris sebagai “benda cagar budaya bergerak”.
Perpres 78/2007 meratifikasi Konvensi UNESCO, memastikan keris dipandang sebagai warisan takbenda yang harus dijaga keberlanjutannya.
Semua ini menunjukkan: keris seharusnya dilihat sebagai pusaka, bukan senjata.
Namun UU Darurat 1951 tetap memberi bayang-bayang kriminalisasi.
Padahal, bila dicermati, undang-undang ini sebenarnya mengatur senjata yang membahayakan keamanan umum—bukan benda pusaka yang dibawa dalam konteks adat, budaya, atau ritual.
Pasal 2 UU Darurat 1951: Ruang Kecil yang Justru Menjadi Kunci
Sering luput dibaca, ayat (2) dari undang-undang ini sebenarnya menyediakan pintu keluar yang sangat penting:
Tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib.
Kalimat inilah yang memberi legitimasi budaya.
Kalimat inilah yang sebenarnya memisahkan keris dari golongan senjata tajam untuk tindak kriminal.
Masalahnya:
Penafsiran di lapangan seringkali tidak sensitif terhadap kebudayaan.
Polisi yang tidak memahami konteks budaya bisa saja menganggap keris sebagai “senjata tajam” hanya karena bentuk fisiknya.
Padahal dalam hukum pidana, intensi (mens rea) dan tujuan penggunaan menjadi elemen penting.
Kunci Penegakan Hukum: Niat, Konteks, dan Kesadaran Budaya
Keris yang dibawa untuk:
upacara adat,
pameran budaya,
koleksi keluarga,
ritual Suro,
atau sebagai bagian identitas leluhur,
tidak dapat dipersamakan dengan keris yang digunakan untuk:
mengancam,
menusuk,
melukai,
atau menjadi alat tindak pidana.
Hukum pidana selalu menuntut dua unsur:
perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea).
Membawa keris tanpa niat jahat—terutama dalam konteks budaya—tidak bisa otomatis dipidana.

(Foto : Dok. Media Ronggolawe News)
Dua Tafsir yang Harus Dipertemukan
Problematika utama hari ini bukan pada kerisnya, tetapi pada perbedaan paradigma antara hukum pidana dan hukum kebudayaan.
Hukum pidana melihat keris sebagai objek berbahaya.
Hukum kebudayaan melihat keris sebagai identitas bangsa.
Dua tafsir ini tidak akan pernah bertemu sampai negara berani memperjelas batasan kontekstual. Selama aparat penegak hukum tidak diberi pemahaman budaya, keris akan selalu berada di wilayah abu-abu yang rawan kriminalisasi.
Kesimpulan: Keris Bukan Sekadar Benda, dan Hukum Tidak Boleh Membutakannya
Keris hari ini bukan lagi alat perang.
Ia adalah artefak budaya yang memuat sejarah, nilai spiritual, estetika, dan legitimasi tradisi.
Maka, menempatkan keris dalam kategori yang sama dengan senjata kriminal jelas merupakan penyempitan makna budaya. Undang-Undang Darurat 1951 memang masih berlaku, tetapi semangat yang terkandung di dalamnya tidak lagi sejalan dengan perkembangan kebudayaan nasional.
Penegakan hukum yang bijak harus mampu membaca:
konteks budaya,
niat penggunaan,
fungsi ritual,
dan nilai pusaka.
Sebab bila keris dipaksa dilihat hanya sebagai “senjata penusuk”, maka hukum modern sedang mengebiri warisan kebesaran Nusantara.
Keris adalah pusaka. Dan pusaka tidak boleh dipertukarkan maknanya dengan senjata kejahatan.